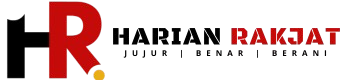Tanah Sultan, Derita Rakyat: Ironi Keistimewaan Yogyakarta


Foto: Ilustrasi, Rabu (30/07/2025)
Oleh Muhammad Arifin
Harian Rakjat, Yogyakarta – Lagi dan lagi, kawulo alit Mataram harus menelan getir sebagai tumbal kekuasaan. Dengan dalih pemanfaatan lahan Sultan Ground (SG), para pedagang dan pelaku usaha kecil di kawasan wisata Pantai Sanglen kini harus angkat kaki. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat telah melayangkan surat tertanggal 21 Juli 2025, memerintahkan seluruh warga pemanfaat lahan untuk segera mengosongkan area tersebut paling lambat Senin, 28 Juli 2025. Jika tidak, pengosongan paksa akan dilakukan.
Ini bukan peristiwa pertama. Sebelumnya, warga Lempuyangan juga mengalami nasib serupa: digusur tanpa ampun. Semua atas nama legitimasi keistimewaan, semua atas nama “pembangunan”. Pertanyaannya, pembangunan untuk siapa?
Keistimewaan yang Menyakitkan
Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini dielu-elukan karena kekhususan budayanya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 memberi landasan hukum atas status keistimewaan, termasuk pengelolaan pertanahan oleh Kraton melalui skema SG (Sultan Ground) dan PAG (Pakualaman Ground). Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Alih-alih menjadi pelindung tanah dan rakyat, keistimewaan justru berubah wujud menjadi alat penggusuran.
Tanah-tanah SG kini lebih banyak mengusir daripada mengayomi. Ia berubah dari ruang hidup menjadi ruang investasi. Kawulo alit yang sekian lama menggantungkan penghidupan dari warung kecil, jasa parkir, dan usaha mikro, harus angkat kaki tanpa kompensasi, tanpa relokasi, tanpa empati.
Ketika Raja Tak Lagi Mengayomi
Dalam falsafah Jawa, seorang raja mengemban tugas hamemayu hayuning bawana — memperindah dan menjaga harmoni dunia. Sultan, dalam posisi simbolik maupun politis, seharusnya menjadi payung pengayom rakyat kecil. Namun hari ini, bayang-bayang keistimewaan itu kian pudar. Surat perintah pengosongan Pantai Sanglen yang ditandatangani atas nama Kraton menunjukkan bahwa kini rakyat tak lagi dipeluk, tapi justru dijauhkan.
Kraton seakan bertransformasi menjadi korporasi, bersekutu dengan pemodal, dan kehilangan roh utamanya sebagai penjaga kebaikan rakyat. Ke mana larinya nilai ngayomi yang selama ini diagungkan? Apakah rakyat hanya dihitung ketika ada upacara adat, tapi dilupakan ketika ada kesepakatan investasi?
Rakyat Kecil Terusir dari Tanahnya
Ironi ini terus berulang. Mereka yang terusir bukanlah perambah liar, bukan pula mafia tanah. Mereka adalah rakyat biasa. Mereka hanya ingin hidup dari apa yang bisa mereka jaga. Di Sanglen, mereka menjaga kebersihan, merawat kawasan, menghidupi pariwisata dengan caranya sendiri. Tanpa sokongan negara, tanpa anggaran pemerintah, mereka membangun dengan tangan sendiri. Kini semua itu dianggap ilegal.
Ketika negara dan Kraton tak hadir saat rakyat membangun, lalu datang dengan tangan besi saat ingin mengambil alih—itu bukan keadilan. Itu perampasan.
Pola Kekuasaan yang Represif
Dari Wadas ke Lempuyangan, dan kini ke Sanglen, pola yang sama terjadi: negara dan kekuasaan lokal menggunakan dalih legalitas untuk mengusir. Surat peringatan, intimidasi halus, hingga pengosongan paksa menjadi alat yang dilegalkan. Ketimpangan didekorasi dengan bahasa pembangunan.
Di satu sisi, slogan-slogan seperti “Jogja Istimewa”, “Wisata Ramah Rakyat”, atau “Budaya Luhur” terus dipromosikan. Di sisi lain, rakyat kecil yang menjadi penjaga budaya dan pelaku utama ekonomi lokal justru disingkirkan. Ini paradoks yang menyakitkan.
Untuk Siapa Keistimewaan Ini?
Di tanah yang katanya istimewa ini, rakyat kecil semakin tak punya tempat. Tanah bukan lagi ruang hidup, tetapi komoditas. Sultan Ground bukan lagi tanah budaya, tetapi instrumen bisnis. Jika keistimewaan hanya berpihak pada modal, lalu untuk siapa tanah ini dijaga?
Kawulo alit sudah terlalu sering jadi korban. Sudah saatnya suara mereka tidak lagi dianggap angin lalu. Kalau keistimewaan hanya menjadi alat untuk mempermudah investasi dan menggusur rakyat, maka kita harus bertanya: apakah ini masih keistimewaan, atau justru bentuk paling halus dari ketimpangan?
Catatan Redaksi :
Warga Pantai Sanglen telah mengajukan keberatan, namun hingga kini belum ada tanggapan dari pemerintah daerah maupun Kraton. Salah satu warga mengatakan, “Kami bukan penjahat. Kami hanya ingin bertahan hidup di tanah sendiri.” Kalimat sederhana itu seharusnya cukup untuk membuka hati—jika memang masih ada hati di balik kekuasaan.
(AR)