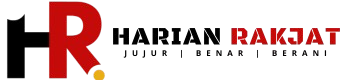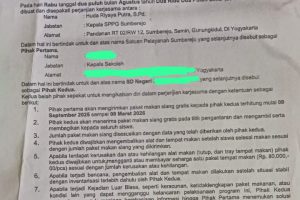Keberadaan Pers di Jogja: Melawan Tirani Dualisme Kepemimpinan
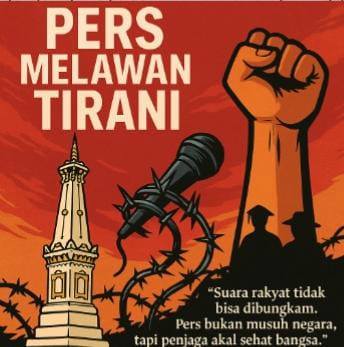

Foto: Ilustrasi
Harian Rakjat, Yogyakarta – Yogyakarta, daerah yang dikenal dengan budaya dan keistimewaannya, menyimpan persoalan mendasar dalam struktur kekuasaannya. Di tengah dominasi simbolik Sultan dan Pakualam, pers lokal diuji: apakah ia tetap menjadi penjaga nalar publik, atau ikut larut dalam euforia simbolisme tanpa ruang kritik?
Pers di Yogyakarta tidak berdiri di ruang hampa. Ia tumbuh di wilayah yang memiliki dua wajah: wajah budaya yang penuh unggah-ungguh, dan wajah kekuasaan yang terpelihara melalui struktur turun-temurun. Ketika Sultan dinobatkan sebagai Gubernur tanpa pemilu, dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur secara otomatis, publik kehilangan satu pilar demokrasi: hak untuk memilih.
UU Keistimewaan No. 13 Tahun 2012 memang mengatur keistimewaan itu, namun hal ini tidak boleh menghapus peran penting pers dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan demokrasi. Di tengah maraknya pembangunan yang menggusur ruang hidup warga, alih fungsi tanah untuk kepentingan investasi, serta konflik agraria di wilayah DIY, suara-suara kritis makin terdengar samar. Pers kerap terjebak menjadi pelengkap seremoni, sekadar membagikan rilis pemerintah, tanpa ruang penyelidikan atau keberanian menyentuh akar masalah.
Dalam kondisi seperti ini, peran pers bukan sekadar menyampaikan informasi. Ia adalah alat demokrasi, sekaligus benteng terakhir masyarakat sipil. Ketika pengawasan institusional tidak berjalan—karena semua jabatan kunci tidak dipilih rakyat—maka harapan tinggal pada suara bebas media.
Namun realitasnya, banyak media lokal di DIY masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan. Ketergantungan terhadap anggaran iklan pemerintah, serta relasi kultural dengan keraton, membuat banyak redaksi memilih diam atau bermain aman. Hal ini sangat berbahaya, karena kekuasaan yang tidak pernah ditantang akan cenderung melampaui batasnya.
Pers seharusnya mengingat akar sejarahnya—sebagai penjaga akal sehat rakyat. Dalam konteks Yogyakarta, ia mesti berani membuka diskusi soal demokratisasi keistimewaan. Bukan untuk menghapus budaya, melainkan untuk memastikan bahwa keistimewaan tidak melahirkan tirani baru yang dibungkus dengan narasi budaya.
Salah satu titik rawan paling krusial adalah jabatan Gubernur DIY yang dipegang oleh Sultan secara seumur hidup tanpa pemilihan langsung. Di tengah semangat demokrasi pasca reformasi, DIY justru mencatat satu-satunya provinsi yang masyarakatnya tidak bisa memilih pemimpin daerahnya secara langsung. Hal ini tidak hanya membatasi partisipasi politik, tapi juga menciptakan ruang kekuasaan absolut yang sulit diawasi.
Jika kekuasaan tanpa kontrol ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan muncul kebijakan-kebijakan elitis yang mengabaikan kepentingan rakyat. Maka, keberadaan pers sebagai penjaga nurani publik menjadi mutlak. Ia harus berani mengangkat suara petani yang tergusur, mahasiswa yang dikriminalisasi saat demonstrasi, atau warga adat yang dilanggar haknya. Itulah esensi dari keistimewaan yang sejati: bukan pada siapa yang berkuasa, tetapi pada siapa yang dibela.
Suara Tajam dari Rakyat:
“Kritik terhadap posisi Sultan sebagai Gubernur seumur hidup bukan berarti anti-keistimewaan. Justru sebaliknya, ini adalah panggilan untuk membangun tata kelola yang adil—di mana kekuasaan tidak abadi, dan rakyat tetap menjadi pusat kedaulatan. Jika tidak, keistimewaan hanya akan menjadi kedok dari kekuasaan absolut yang luput dari kontrol publik.” (AR).