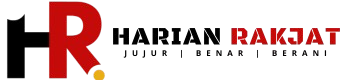Saptosari: Menjaga Warisan, Menghidupkan Pariwisata
 Oplus_131072
Oplus_131072 
Foto: Ilustrasi
Oalah: Muhammad Arifin
Harian Rakjat, Gunungkidul – Sabtu (23/08/2025), Kapanewon Saptosari di pesisir selatan Gunungkidul dikenal bukan hanya karena bentang alamnya yang indah, tetapi juga karena kekayaan tradisi dan budaya yang melekat di tengah kehidupan warganya. Tercatat ada 60 padukuhan di wilayah ini, masing-masing dengan kearifan lokal yang hampir serupa: adat, kesenian, serta rasa gotong royong yang menjadi denyut nadi masyarakat pedesaan.
Salah satu tradisi yang paling menonjol ialah Labuhan Pantai Ngrenehan. Setiap bulan Suro atau 1 Muharam, nelayan dan warga menggelar upacara syukur atas rezeki laut. Hasil tangkapan ikan dipersembahkan secara simbolis sebagai bentuk pengakuan bahwa laut bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga ruang sakral yang harus dihormati.
Selain Labuhan, hampir di semua padukuhan masih lestari adat Rasulan atau Bersih Dusun. Tradisi ini menjadi momentum perekat sosial, memperkuat rasa persaudaraan, dan mengingatkan bahwa manusia tak pernah hidup sendirian. Sementara itu, di ranah kesenian, Saptosari tetap hidup dengan jathilan, wayang, reog, hingga gejog lesung, yang sering hadir dalam hajatan warga.
Lebih dari itu, Saptosari juga dianugerahi destinasi wisata yang beragam. Pantai Ngrenehan, Ngobaran, dan Nguyahan menjadi ikon wisata bahari dengan panorama pasir putih dan debur ombak yang menawan. Ada pula Goa Jepang yang menyimpan jejak sejarah, serta Gunung Gambar dengan potensi wisata alam dan spiritualnya. Harmoni antara pesona alam dan tradisi budaya inilah yang membuat Saptosari berbeda dengan kawasan lain di Gunungkidul.
Namun, di tengah arus modernisasi dan pariwisata yang terus berkembang, muncul pertanyaan: apakah tradisi ini akan tetap lestari atau perlahan terkikis menjadi sekadar tontonan wisata? Jangan sampai kearifan lokal hanya dijadikan komoditas tanpa makna, kehilangan ruh spiritual dan sosialnya.
Inilah tantangan besar bagi Saptosari: mengembangkan wisata berbasis budaya tanpa mengorbankan nilai asli tradisi. Pemerintah, tokoh adat, dan generasi muda harus bergandengan tangan. Tradisi Labuhan bisa menjadi magnet wisata religi-budaya; Rasulan bisa dikemas sebagai festival rakyat; kesenian tradisional bisa dihidupkan kembali melalui sanggar dan pertunjukan reguler; dan destinasi alam perlu dikelola dengan bijak agar tak rusak oleh eksploitasi.
Saptosari telah memiliki modal besar berupa kearifan lokal dan keindahan alam. Yang dibutuhkan kini adalah strategi pelestarian dan promosi yang arif. Tradisi jangan hanya jadi tontonan, tetapi tetap menjadi tuntunan. Dengan begitu, Saptosari bukan hanya dikenal karena pantainya, tetapi juga sebagai tanah budaya yang hidup dan berdaya.
(AR)