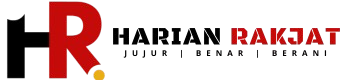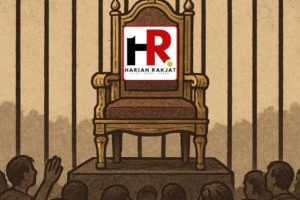Outsourcing, Kepentingan Siapa?
 Oplus_131072
Oplus_131072 
Foto: dok.pribadi Awang Raga Gumilar
Oleh: Awang Raga Gumilar, S.H.
Harian Rakjat, Yogyakarta – Selasa, 19 Agustus 2025, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Serap Aspirasi untuk Penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, ada rasa gatal yang mendorong Penulis untuk mengulas kembali isu outsourcing. Entah di kolom komentar, forum, maupun diskusi live, outsourcing hampir selalu dipandang jahat.
Bahkan, seorang kawan, rambutnya sudah memutih dan umurnya jauh di atas Penulis, dengan tegas menyebut outsourcing sebagai bentuk perbudakan modern. “Harus dihapuskan,” katanya. Dalam hati, Penulis membatin: beliau sudah lebih lama hidup, pasti ada benarnya dalam ucapan itu.
Mengenal Istilah dan Aturannya
Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya Penulis menyisipkan beberapa catatan:
1. Istilah “outsourcing” sebenarnya tidak pernah disebut dalam aturan hukum Indonesia.
Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang ada hanyalah istilah Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Kata “outsourcing” sendiri berasal dari bahasa asing, kemudian diserap oleh kalangan pengusaha Indonesia agar terdengar lebih keren dan ringkas.
2. Istilah baru muncul dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pada 2 November 2020, istilah lama diganti menjadi Alih Daya.
3. Perusahaan Alih Daya wajib membuat Perjanjian Alih Daya dengan User atau Prinsipal.
Poin ketiga inilah yang Penulis ingin soroti, karena justru di sinilah letak persoalannya.
Alih Daya dalam Regulasi
Omnibuslaw yang kini telah disulap menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 memang sudah mengatur soal Alih Daya. Namun, pengaturannya masih terasa “impoten”.
Memang benar, regulasi mewajibkan adanya Perjanjian Alih Daya. Akan tetapi, tidak ada kejelasan mengenai hal-hal apa saja yang wajib dimuat di dalamnya. Padahal, sebagai regulator, Pemerintah seharusnya menetapkan batas minimal yang jelas.
Sebagai perbandingan, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan tegas mewajibkan bahwa Perjanjian Kerja harus memuat identitas dasar pekerja, seperti nama, jenis kelamin, dan umur. Bahkan, urusan kelamin pun diatur. Lalu, bagaimana dengan Perjanjian Alih Daya yang melibatkan ribuan pekerja? Mengapa justru dibiarkan longgar?
Praktik di Lapangan
Jika kita membuka situs tender pemerintah, jasa pengamanan dan kebersihan hampir selalu muncul sebagai kebutuhan berbagai Kementerian, Lembaga, maupun Instansi. Artinya, negara sendiri pun menjadi User dari praktik alih daya ini.
Di titik ini, muncul pertanyaan reflektif:
Jika Perjanjian Alih Daya diatur secara rinci dan rigid, maka ruang gerak User, termasuk pemerintah, tentunya akan semakin sempit.
“Semakin ke sini kok semakin begini, ya?” gumam Penulis dengan heran.
(AR)